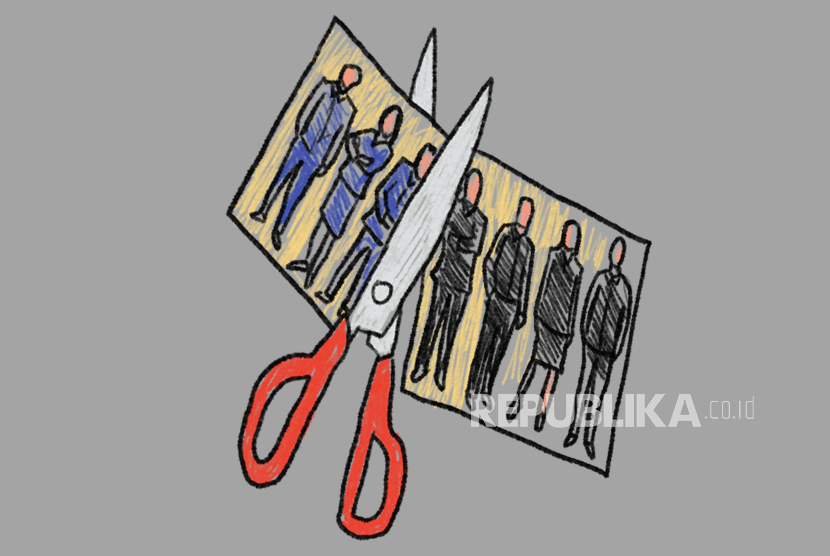
medkomsubang.CO.ID, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (LBH Sarbumusi) prihatin atas gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang kini melanda berbagai sektor di Indonesia, mulai dari manufaktur, digital, hingga tekstil dan startup – yang tidak hanya mengorbankan para pekerja formal, melainkan juga pekerja non-formal dan informal.
Data PHK teraktual menunjukkan skala krisis yang memprihatinkan: Per bulan Mei 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan jumlah PHK mencapai 26.455 kasus. Provinsi yang menyumbang kasus PHK paling tinggi adalah Jawa Tengah. Berbeda dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mencatat jumlah PHK telah mencapai 73.992 kasus per bulan maret 2025. Apindo bahkan memproyeksikan bahwa lebih dari 250.000 pekerja akan terkena PHK sepanjang 2025.
Jumlah data tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2025 yang secara rata-rata jauh lebih besar dibandingkan tahun 2022-2024. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan, klaim JKP hingga April 2025 mencapai 52.850 klaim (13.210 klaim JKP/bulan).
Kami berpandangan, krisis PHK ini bukan hanya soal statistik, melainkan dampak sistemik yang menggerus kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia, pada Mei 2025, telah mengingatkan bahwa tren PHK ini bisa menjadi rem darurat bagi pertumbuhan nasional.
Reaktif Tanpa Antisipatif
Alih-alih mengevaluasi sistem ketenagakerjaan dan membenahi iklim industri, Pemerintah secara reaktif justru kembali mengambil jalan pintas simbolik dengan menginisiasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) sebagai dalih aspiratif menyikapi gelombang PHK.
LBH Sarbumusi melihat respons pemerintah melalui pembentukan Satgas PHK dan DKBN sebagai langkah populis dan tidak menyentuh jantung persoalan struktural. Berikut 9 catatan evaluatif LBH Sarbumusi terhadap inisiasi reaktif tersebut:
Pertama sindrom satganisasi dan ketidakpercayaan diri pemerintah
Pembentukan Satgas PHK adalah gejala "sindrom satganisasi"—respons populis jangka pendek untuk menambal masalah sistemik. Ini secara telanjang menandakan bahwa pemerintah tidak percaya diri terhadap birokrasi ketenagakerjaan yang dimiliki negeri ini, padahal Kementerian Kemenaker memiliki struktur berjenjang secara nasional hingga tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.
Kedua , redundansi kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan
Karakteristik DKBN tumpang tindih dengan Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, dan Komite Jaminan Sosial Nasional. Sementara itu, Satgas PHK turut menduplikasi kerja Pengawas Ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial. Alih-alih mengevaluasi dan memperkuat sistem kelembagaan yang sudah ada, langkah ini justru memperlemah kejelasan struktur dan memboroskan anggaran negara yang saat ini gencar melakukan efisiensi. Pasal 175 dan 176 UU Ketenagakerjaan secara tegas telah menetapkan pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaan sebagai tugas pemerintah melalui pejabat pengawas ketenagakerjaan pusat hingga daerah.
Tiga , jangan menyentuh akar dan krisis perlindungan
Gelombang PHK terjadi bukan karena lemahnya koordinasi, melainkan akibat kebijakan deregulatif pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, kontrak fleksibel tanpa batas, dan lemahnya sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Satgas PHK dan DKBN tidak menyentuh akar persoalan ini, menjadikannya sekadar simbol tanpa daya perubahan struktural.
Keempat , memperpanjang alur birokrasi dalam penanganan
Pembentukan Satgas PHK dan DKBN justru menambah mata rantai baru dalam birokrasi ketenagakerjaan. Kini, muncul entitas baru yang tidak jelas posisi fungsionalnya dalam rantai pengambilan keputusan, padahal sebelumnya buruh atau pengusaha cukup berurusan dengan pengawas ketenagakerjaan, mediator, atau dinas tenaga kerja. Pola ini jelas akan bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta berpotensi mengaburkan asas non-duplicity.
Kelima mengaburkan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan buruh:
Dengan membentuk organ baru, negara cenderung "memindahkan" tanggung jawab kesejahteraan pekerja pada forum-forum ad hoc, bukannya memperkuat peran regulator formal. Ini justru menjauhkan buruh dari akses keadilan, memperlemah pengawasan, dan memicu krisis kepercayaan terhadap negara.
Enam , menekankan kebutuhan reformasi struktural, bukan solusi sementara
Solusi terhadap krisis PHK dan kesejahteraan buruh harus berbasis pada reformasi sistem pengupahan, perluasan jaminan sosial, penguatan pengawasan, dan keberpihakan anggaran. Satgas PHK dan DKBN hanya menutupi absennya kemauan politik untuk melaksanakan reformasi tersebut secara menyeluruh dan berkeadilan.
Ketujuh , mengabaikan dimensi kesejahteraan dan kesehatan mental pekerja
Satuan tugas tidak memiliki pendekatan psikososial terhadap buruh yang kehilangan pekerjaan, padahal trauma pemutusan hubungan kerja sangat nyata dan berpotensi menjadi faktor kriminogen atau pencetus kriminalitas.
Kedelapan , berpotensi menambah akumulasi kegagalan lembaga negara Ad Hoc
Pembentukan Satgas PHK dan DKBN hanya akan menambah panjang daftar lembaga negara ad hoc yang dibentuk secara reaktif, tanpa desain kelembagaan yang jelas, tidak akuntabel, dan akhirnya gagal menjalankan mandat substantifnya. Ini mencerminkan defisit tata kelola kelembagaan (defisit tata kelola institusi) yang kian akut.
Sembilan dapat digunakan sebagai instrumen politik dan melemahkan gerakan buruh
Berangkat dari tidak terbangunnya melalui partisipasi yang bottom-up dan mekanisme transparan, Satgas PHK dan DKBN rawan dijadikan alat legitimasi elit, bukan alat perjuangan buruh. Ini membahayakan prinsip independensi gerakan buruh sendiri.
Negara telah kembali menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengantisipasi dan menanggulangi fenomena krisis yang menyebabkan memudarnya legitimasi pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusional bagi pekerja/buruh sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 (2), 28D (2), dan 28H (1) UUD 1945.
LBH Sarbumusi mendesak pemerintah segera mengevaluasi kembali keputusan pembentukan Satgas PHK dan DKBN. Prioritas utama seharusnya adalah penguatan kelembagaan Kemenaker, reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang substansial, perluasan jaring pengaman sosial yang memadai, dan pemulihan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Tanpa adanya reformasi struktural yang mendalam dan keberanian politik untuk mendukung buruh/pekerja, krisis PHK ini akan terus menjadi rem darurat bagi pertumbuhan nasional dan mengancam stabilitas sosial-ekonomi bangsa.


